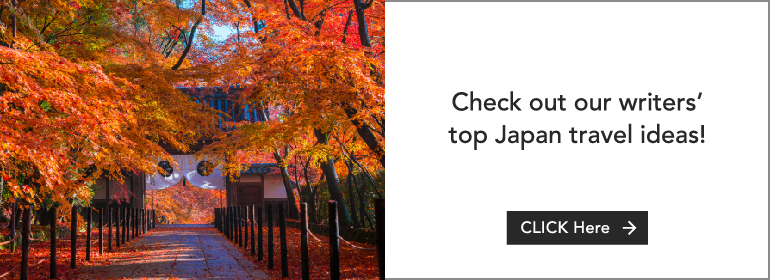Wabi Sabi: Filosofi Jepang Tentang Keindahan Dalam Ketidaksempurnaan
Pernahkah Anda tertarik pada sebuah barang di jendela toko yang berdebu? Atau mungkin Anda pernah membenamkan diri di alam bebas dan menyaksikan waktu berlalu dengan ritme alaminya? Jika Anda mengalami hal tersebut, berarti secara tidak sadar Anda telah memahami wabi sabi. Filosofi Jepang yang menerima ketidakabadian dan ketidaksempurnaan dalam hidup ini juga membantu melahirkan beberapa bentuk seni paling terkenal di negara itu. Baca terus untuk mengetahui makna wabi sabi dalam estetika tradisional dan bagaimana masyarakat Jepang menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
This post may contain affiliate links. If you buy through them, we may earn a commission at no additional cost to you.
Apa Itu Wabi Sabi? Keindahan Dalam Ketidaksempurnaan
Dari contoh di bagian pendahuluan, Anda mungkin bisa menyimpulkan bahwa wabi sabi cukup sulit dijelaskan secara singkat. Namun, dengan melihat lebih dekat pada asal kata dan memecahnya menjadi dua bagian, kita dapat lebih memahami wabi sabi.
Istilah wabi sabi sebenarnya berasal dari dua kata yang disatukan. "Wabi" aslinya memiliki beberapa arti, yakni "kesedihan", "penderitaan", atau "kekosongan", sedangkan "sabi" menggambarkan "kemunduran" atau sesuatu yang "tidak bersemangat".
Meskipun makna wabi dan sabi membangkitkan perasaan melankolis karena mengandung kesedihan atau arti negatif dalam bahasa Indonesia, kata wabi sabi memunculkan kehangatan dan kehidupan dalam bahasa Jepang seperti yang akan kami jelaskan di bagian selanjutnya.
Asal-Usul "Wabi"
Seiring berkembangnya frasa ini, "wabi" mulai diterjemahkan menjadi sesuatu yang mendefinisikan perasaan "menghargai kesederhanaan atau keadaan alami". Menurut seorang filsuf bernama Alan Watts, wabi merepresentasikan kesendirian atau kesepian.
Sementara itu, Kazuo Okakura - penulis The Book of Tea, memiliki interpretasi lain terhadap kata wabi. Bukunya sengaja ditulis dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan budaya teh Jepang ke Barat (yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang setelah meraih kesuksesan di Barat). Di buku tersebut, Okakura mendeskripsikan wabi sebagai "ketidaksempurnaan" atau "tidak rampung", tetapi dengan potensi peningkatan. Ada perasaan yang mendasari ketidaksempurnaan ini, hanya saja lebih kepada sentimen "apa yang akan terjadi maka terjadi".
Penyebutan wabi oleh seorang master teh bukanlah suatu kebetulan karena wabi sangat erat kaitannya dengan wabi-cha, jenis upacara minum teh khusus yang dikembangkan di Jepang. Kami akan membahas tentang ini nanti. Sekarang, mari kita beralih ke "sabi".
Asal-Usul "Sabi"
"Sabi" berasal dari kata kerja "sabu", yang berarti memburuk atau kehilangan kilau seiring waktu. Namun, hal ini tidak selalu berarti buruk karena dapat menyiratkan kehangatan dan keakraban pada sesuatu seperti barang antik. Kata sabi berangsur-angsur diasosiasikan dengan tempat-tempat sunyi tanpa kehadiran manusia. Bukankah itu terdengar tidak masuk akal? Bagaimana bisa kita merasa betah di tempat yang tidak ada manusia? Melalui paradoks inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sabi menyerupai kesunyian dan keheningan seseorang ketika menyaksikan segala sesuatu yang berjalan sesuai hukum alam.
Ajaran Buddha, Haiku, dan Keindahan Fana dari Ketidakabadian
Wabi sabi juga berkaitan dengan Zen Buddhisme dan tercermin dalam bentuk puisi Jepang yang dikenal sebagai "haiku". Penyair terkenal Matsuo Basho menulis baris-baris puisi yang menggambarkan keadaan kolam yang tenang bergema karena katak menyelam ke dalam air; makam prajurit yang terlupakan dikelilingi oleh rerumputan tinggi; atau batu sunyi di tengah suara jangkrik. Melalui haiku-nya, Basho menangkap perasaan sabi yang mengekspresikan keheningan, keindahan alam, berlalunya waktu, dan sifat kehidupan yang terus berubah.
Perasaan tersebut memiliki ikatan kuat dengan ajaran Buddha terkait kehidupan. Dalam hidup, kita semua menghadapi tiga hal yang tidak terhindarkan: Kefanaan, penderitaan, dan kekosongan. Alih-alih mengasihani diri sendiri, wabi sabi menyarankan kita untuk menerima dan membangun pandangan hidup yang lebih positif. Jika tidak dapat dihindari, nikmatilah, dan temukan kedamaian dalam melepaskannya.
Wabi Sabi Dalam Upacara Minum Teh Jepang, Wabi-cha
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana kata tersebut berhubungan dengan upacara minum teh Jepang yang disebut "wabi-cha" (juga dikenal sebagai "sado" atau "chado"). Upacara wabi-cha menekankan pada kesederhanaan dan menunjukkan apresiasi terhadap hal-hal di sekitar sebagaimana adanya (seperti yang dijelaskan di atas, wabi mewakili 'kesederhanaan', sedangkan cha berarti 'teh'). Wabi-cha dilakukan secara sederhana tanpa terlalu banyak kemegahan dalam suasana upacara minum teh gaya Tiongkok yang populer.
Di masa lalu, upacara minum teh gaya Tiongkok yang mewah sebenarnya sangat populer di Jepang. Diadakan oleh para elite sosial selama zaman Muromachi (tahun 1300 hingga 1500-an) sebagai cara untuk menunjukkan kelas dan kekuasaan mereka.
Namun, sulit untuk menghindari perbedaan pandangan mengenai cara-cara yang sudah mengakar dalam melakukan sesuatu. Begitu pula dengan wabi-cha, yang lahir dari inspirasi seorang biksu bernama Murato Juko yang mencari cara lebih tenang dan sederhana untuk menikmati teh. Alih-alih menggunakan porselen mewah dari Tiongkok, ia memperkenalkan penggunaan cangkir teh tanah liat Jepang, yang dibuat dengan tangan dan sering kali ada cacat kecil dalam bentuk atau desainnya. Dari lahirnya wabi-cha inilah filosofi dan istilah wabi sabi mulai menyebar.
Cacat dan Rusak, Menghargai Ketidaksempurnaan
Murato Juko juga merupakan orang yang menciptakan alat-alat untuk upacara minum teh dan menggabungkan wabi-cha dengan semangat Zen Buddhisme. Murato mendeskripsikan "wabi" sebagai berikut: "... keindahan bulan lebih menonjol ketika memudar di balik awan". Singkatnya, wabi dapat diartikan mengejar keindahan yang tidak sempurna.
Seperti kata pepatah, "kecantikan ada di mata yang melihatnya", dan "tidak ada yang sempurna". Wabi sabi menawarkan kepada kita cara untuk menghargai berbagai bentuk keindahan bukan melalui pesonanya, melainkan melalui ketidaksempurnaannya. Membawa objek atau pengalaman lebih dekat dengan kenyataan, dan membuatnya lebih menarik dan berwarna.
Retakan dalam Keindahan Wabi Sabi: Kintsugi dan Lahirnya Emas
Wabi sabi sering diasosiasikan dengan cangkir dan mangkuk teh, tetapi dengan cara yang sangat istimewa. Meskipun tren menyingkirkan kemewahan Tiongkok menghasilkan secangkir teh alami dan tidak sempurna yang populer di Jepang, konsep wabi sabi mengambil lapisan yang lebih dalam setelah wadah rusak ini pecah.
Ketika sebuah tembikar pecah, mayoritas orang langsung berpikiran untuk membuangnya dan membeli yang baru. Bertolak belakang dengan pemikiran wabi sabi yang melihat peluang kehidupan baru melalui proses "kintsugi". Oleh karena itu, orang akan memperbaiki mangkuk yang pecah menggunakan lem yang dicampur dengan bubuk emas untuk menghidupkan kembali barang tembikar tersebut.
Kintsugi disebut sebagai perwujudan konsep dari wabi sabi. Penggunaan logam mulia seperti emas untuk menonjolkan retakan dan ketidaksempurnaan adalah bukti hidupnya kembali suatu objek, menarik perhatian orang pada ketidaksempurnaan, bukan menyembunyikannya. Mangkuk teh yang diperbaiki secara khusus ini umumnya memiliki harga lebih tinggi daripada mangkuk baru. Kintsugi pernah begitu populer sehingga beberapa seniman sengaja memecahkan mangkuk mereka sendiri untuk menciptakan versi perbaikan yang sedang digemari. Namun, ironisnya semua tindakan itu menyebabkan hilangnya seluruh inti dari kintsugi dan wabi sabi.
Kesimpulan
Wabi sabi seolah memberikan harapan di dunia modern, ketika media sosial memproyeksikan kehidupan yang sempurna melalui foto-foto editan. Wabi sabi justru sebaliknya, konsep ini mendorong orang untuk hidup sederhana, mengedepankan ketenangan pikiran, serta lebih menghargai sesuatu yang sudah lama dibandingkan yang baru. Jadi, saat Anda merasa stres, cobalah seduh teh hangat, gunakan cangkir favorit Anda, dan luangkan waktu untuk melihat dunia yang terbentang di hadapan Anda.
Sebagai tambahan, ada budaya Jepang lainnya yang juga berkaitan dengan wabi sabi dan kintsugi, yaitu cerita rakyat Jepang tentang tsukumo-gami. Tsukumo-gami adalah benda mati, yang setelah 100 tahun digunakan atau bersentuhan dengan manusia, diyakini memiliki jiwanya sendiri. Objek itu bisa berupa apa saja, seperti cermin tua yang berdebu, palu berkarat, atau bahkan mangkuk teh yang retak dan sudah diperbaiki. Meskipun tsukumo-gami pada dasarnya merupakan makhluk dongeng, keberadaannya dalam cerita rakyat menunjukkan manfaat dari tindakan merawat benda mati favorit Anda.
Jika Anda ingin memberikan komentar pada salah satu artikel kami, memiliki ide untuk pembahasan yang ingin Anda baca, atau memiliki pertanyaan mengenai Jepang, hubungi kami di Facebook!
The information in this article is accurate at the time of publication.